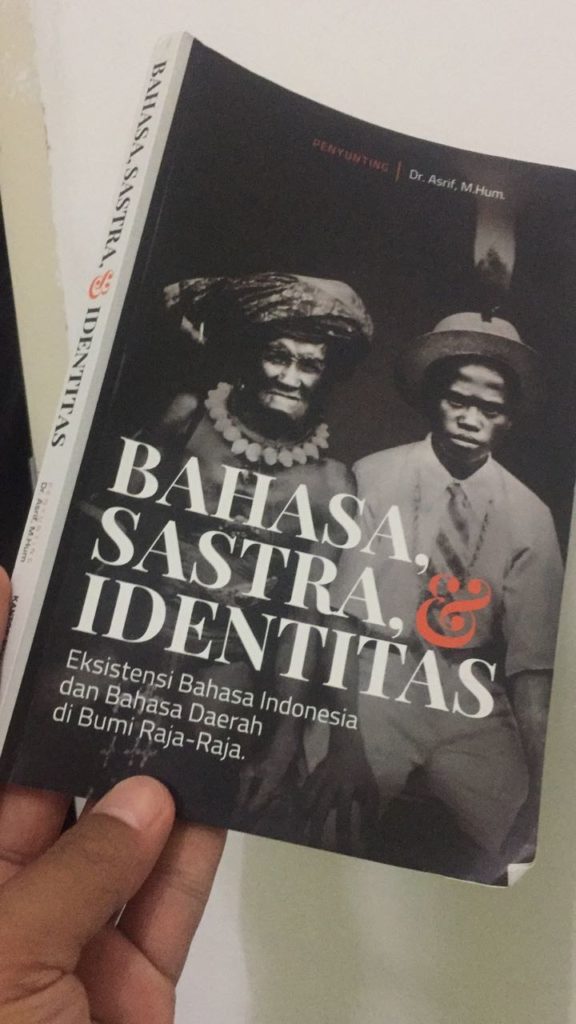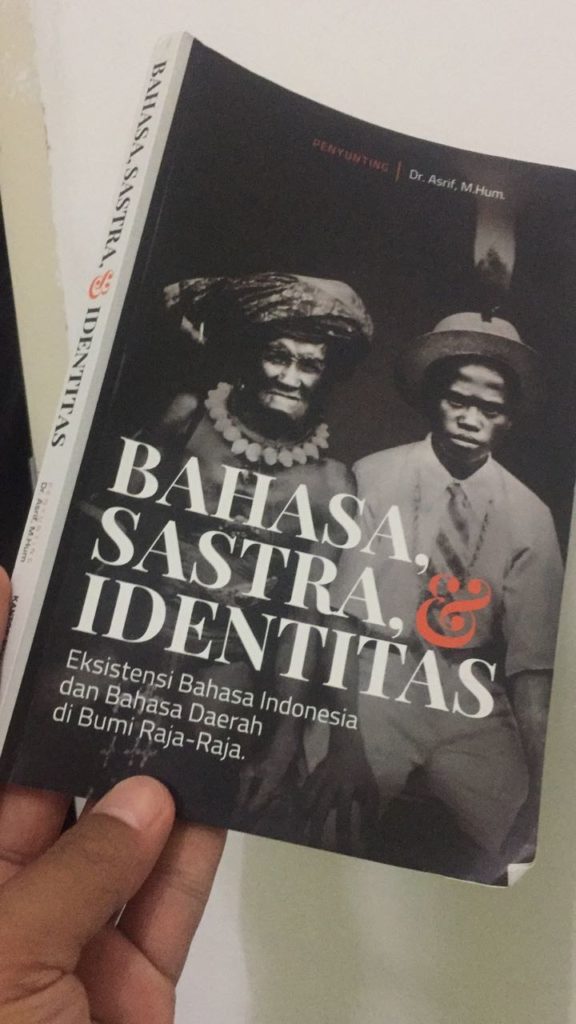
Hari ke-11 & 12 di Seram Bagian Barat
Saya seperti baru sadar. Selama berada di Seram Bagian Barat, belum satu buku pun yang saya tamatkan. Wah seorang penulis yang katanya berkarya di suatu daerah dalam program kepenulisan tapi malah tidak membaca buku selama masa penugasan, tidakkah ini aib yang dengan polos saya buka di sini?! Ya, buku terakhir yang saya baca adalah Cerita Meksiko yang ditulis Azhari Aiyub, alumnus Program Sastrawan Berkarya Angkatan I (2016). Itu pun ketika saya masih berada di Wisma Badan Bahasa alias sebelum bertolak ke Piru.
Maka, Ahad kemarin (21-4-2018) saya memilih libur. Saya pikir, ada baiknya saya membuat semacam jeda bagi perjalanan ini. Lagi pula, sepulang dari Kaibobo kemarin, sisa pegal-pegal di badan saya belum juga hilang hingga pagi ini. Saya mengontak Bang Reimon dan mengutarakan hal itu. Saya perlu melakukannya sebab kehadiran beliau di lobi hotel setiap pagi sudah menjadi rutinitasnya sejak menjadi pendamping saya di program badan bahasa ini. Saya tak ingin dia datang pagi ini sementara saya belum bersiap-siap sebab memang saya sedang tidak ingin ke mana-mana. Ya, dedikasi dan tanggungjawab yang melekat pada diri Bang Reimon dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Bagian Humas Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat untuk mendampingi saya sungguh tidak perlu diragukan. Sebagaimana biasa, laki-laki 45 tahun itu tidak banyak bicara. Ia mengerti dan menyisipkan peringatan di ujung telepon, “Bang Ben jangan makan terlalu banyak durian!” Ia hafal sekali rupanya. Sejak hari ke-4 di Piru, tidak satu hari pun yang saya lewatkan tanpa melahap 2-4 durian.
Dari sekitar enam buku yang saya bawa ke Piru, saya justru memilih buku yang mulanya tidak saya siapkan untuk menemani proses kreatif saya di sini. Pagi Ahad kemarin saya justru memilih “Bahasa, Sastra, dan Identitas”, kumpulan esai kebudayaan yang diterbitkan Kantor Bahasa Maluku (2016). Bunga rampai esai yang ditulis sejumlah mahasiswa di Maluku itu disunting langsung oleh kepala Kantor Bahasa Maluku, Dr. Asrif M. Hum. Saya mendapatkannya sebagai buah tangan usai saya mengisi materi penulisan kreatif bagi empat puluh guru bahasa Indonesia kabupaten ini dua hari yang lalu. Sampulnya yang klasik langsung membetot urat kepenasaran saya. Belakangan saya tahu kalau potret hitam putih dua orang–yang mulanya saya pikir adalah ibu dan anak–di sampul buku adalah ayah dan anak. Penutup kepala yang dikenakan sang ayah yang mirip lipatan kain ibu-ibu Melayu selintas lalu membuatnya tertangkap pandang sebagai perempuan, sebagai ibu. Foto yang diberi judul “Father and Son” itu ternyata dipetik fotografer Petrus Drabbe pada tahun 1930 dan diunduh dari sebuah situs di internet. Semoga kebermanfaatan hasil karyanya untuk sebuah buku kebudayaan, sedikit banyak, memberikan Drabbe sedikit kegembiraan ‘di sana’.
Namun, sebagaimana biasa, memulai kebiasaan yang sempat terabaikan itu membuat saya susah fokus. Saya malah menyelingi pembacaan saya dengan buku-buku lain. Alhasil, kumpulan esai kebudayaan itu pun hanya saya baca seperempatnya. Sebenarnya bukan semata godaan buku-buku lain. Keinginan saya untuk ‘mengubek-ubek’ pasar kota dan pasar pantai Piru juga menjadi pemicunya. Di tengah niat untuk mengkhatamkan sebuah bahan bacaan, sebuah keinginan tiba-tiba menyeruak. Saya tiba-tiba merindukan makan pisang ambon!
Memang, di rumah saya, buahan itu nyaris tidak pernah absen ada di atas meja makan kami. Saya bisa menghabiskan satu sikat kalau sedang ingin-inginnya. Di sini, di provinsi yang ibukotanya bernama Ambon, bagaimana bisa saya lidah saya tidak mencicipi pisang ambon barang sebuah pun, beuh!
Ahad itu pun, saya gagal menamatkan sebuah buku, sebagaimana saya gagal menemukan pisang ambon yang oleh masyarakat setempat disebut pisang meja. “Jadi di mana saya bisa mendapatkannya, Mama?” tanya saya pada salah seorang penjual yang memasang muka ramah.
“Tunggu ada yang jual, Kaka,” jawabnya ramah dan ‘tanpa dosa’.
Tunggu ada yang jual?! Waduh! Mama, takkah kau lihat muka Hamba yang ngidam pisang ambon!–teriak saya dalam hati sebelum kemudian saya refleks menepuk kening, seakan-akan mengingatkan kalau saya sedang berada di Piru, bukan di Lubuklinggau. Daging pisang ambon yang legit dan aromanya yang khas itu pun hanya bisa saya simpan dalam kepala.
Dan … jadilah Senin (22-4-2018) adalah salah satu hari yang menggembirakan. Ya, saya telah menamatkan buku terbitan Kantor Bahasa Maluku itu! Meskipun itu artinya saya mengambil tambahan satu hari libur, namun sebenarnya saya tidak menghabiskan seharian penuh untuk membaca. Saya sempat menulis sebuah jurnal terkait perjalaanan saya ke Kaibobo dua hari yang lalu. Libur yang tidak sia-sia. Begitu saya menamai dua hari tanpa bepergian itu.
“Bahasa, Sasta, dan Identitas” yang membahas eksistensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Provinsi Maluku itu, kalau saya boleh menyebutnya, adalah narasi panjang tentang kekhawatiran generasi muda (baca: mahasiswa) terhadap turunnya kebanggaan dan minat masyarakat setempat dalam menggunakan bahasa daerah karena pengaruh televisi dan ‘aliran Jakartanisme’ yang menjangkiti kawula muda, bahasa Indonesia yang diabaikan (bahkan oleh pemerintah daerah) dalam penamaan landmark kota atau bangunan publik sebab bahasa Inggris menjadi pilihan utama atas alasan tuntutan zaman, fenomena penggunaan media sosial yang kebablasan sehingga bahasa seperti kehilangan izzah dan fitrahnya sebagai peranti utama komunikasi, bahkan memelipir pada ekspansi bahasa di wilayah ekonomi kreatif. Melihat sebaran topik-topik yang disajikan para penulis, “sastra” yang tertera di judul rasanya tidak muncul di dalam buku. Memang ada salah dua artikel yang menggunakan kata “sastra” pada judulnya, namun bahasannya ternyata begitu permukaan. Wacananya terasa sangat mengawang-awang. Apalagi ketika memaksa-kaitkannya dengan ekonomi kreatif. Setahu saya, hingga hari ini, Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) belum/tidak pernah melirik sastra, apalagi menjadikannya sebagai komoditas ekonomi kreatif seperti yang dikondisikan para penulis dalam buku ini. BeKraf, sejauh ini, ‘lebih sibuk’ dengan arsitektur, kerajinan tangan, tekstil, desain produk dan busana, desain interior, fotografi, videografi, hingga memelipir ke tari dan musik. BeKraf ‘berani’ melakukan ekspansi pada wilayah-wilayah yang “selintas-lalu’ bukan menjadi domainnya seperti film yang sejatinya garapan Pusat Pengembangan Film (Pusbangfilm) atau tari dan musik yang biasanya masuk ke ranah kesenian dan kebudayaan yang diurus oleh Direktorat Kesenian atau direktorat yang bersinggungan lainnya, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), namun tidak sedikit pun ‘menganggap’ sastra!
Namun, tentu saja jurnal ini tidak akan membahas tumpang-tindih tupoksi sejumlah lembaga atau instansi pemerintahan yang mengurusi hajat hidup kebudayaan. Narasi di atas sekadar pemancing wacana untuk membuka cakrawala berpikir kritis tentang bagaimana terpinggirkannya sastra oleh BeKraf. BeKraf tidak menganggap sastra sebagai salah satu cabang kesenian yang hendak mereka rangkul. Nah, buat apa kita berkoar-koar dengan mencocokkan sastra dengan prinsip-prinsip ekonomi kreatif sedangkan badan yang mengurusi hal itu sedikit pun tidak menganggap sastra sebagai bagian darinya? Dua tulisan dalam buku ini mungkin akan terasa ‘bekerja’ ketika bertendens untuk memberikan masukan (baca: kritik) tergadap BeKraf, bukan memaksa-kondisikannya dalam konteks artifisial sebagaimana yang mereka tulis.
Terlepas dari aroma sastra yang hanya numpang lewat saja, buku ini sebenarnya memuat pandangan-pandangan naratif-persuasif tentang bagaimana menyikapi kepunahan bahasa daerah dan nasionalisme yang rapuh di waktu yang bersamaan, sebab semua penulisnya, menulis dengan struktur penulisan esai yang tertib. Selalu ada usulan pemecahan masalah dan kesimpuan di akhir tulisan. Jenis esai begini, sangat membantu pembaca untuk menandai muatan-muatan penting di dalamnya, meskipun di sisi lain ia menjadi kaku dan kurang mengalir. Setidaknya itu yang saya rasakan ketika ‘merampungkan’ buku setebal 179 halaman itu.*